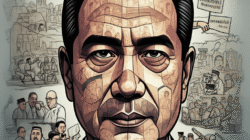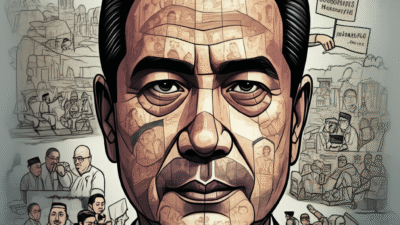Keadilan di Persimpangan: Ketika Hukum Tersandera Politik di Indonesia
Hukum adalah pilar utama sebuah negara beradab, fondasi yang menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak setiap warga negara. Idealnya, hukum berdiri tegak di atas semua kepentingan, tanpa pandang bulu, objektif, dan imparsial. Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, idealisme ini seringkali diuji, bahkan terkikis, ketika hukum justru dijadikan alat ampuh untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan politik tertentu. Fenomena ini, yang dikenal sebagai politisasi hukum, adalah ancaman serius bagi demokrasi dan supremasi hukum itu sendiri.
Hukum: Idealnya Pelindung, Realitanya Senjata
Dalam tatanan ideal, hukum adalah perisai bagi yang lemah, pedang keadilan bagi yang tertindas, dan penyeimbang kekuasaan. Ia bekerja berdasarkan prinsip-prinsip universal seperti kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), due process of law, dan presumption of innocence. Namun, ketika hukum masuk ke dalam arena politik yang sarat intrik dan perebutan kekuasaan, karakternya bisa berubah drastis. Ia bukan lagi alat penegak keadilan, melainkan senjata yang digunakan untuk menyerang lawan politik, membungkam kritik, atau bahkan melegitimasi tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak etis atau melanggar hak asasi manusia.
Mekanisme Politisasi Hukum di Indonesia
Politisasi hukum di Indonesia dapat terjadi melalui berbagai mekanisme yang halus maupun terang-terangan:
-
Penerapan Hukum Tebang Pilih (Selective Enforcement): Ini adalah modus paling umum. Kasus-kasus hukum yang melibatkan pihak yang berkuasa atau sekutunya cenderung lambat diproses, bahkan dihentikan, sementara kasus serupa yang melibatkan lawan politik atau kritikus ditangani dengan cepat dan tegas. Hal ini menciptakan kesan bahwa keadilan hanya berlaku untuk sebagian orang.
-
Kriminalisasi Lawan Politik: Pasal-pasal karet dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau pasal-pasal pencemaran nama baik, seringkali disalahgunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang vokal mengkritik kebijakan atau figur penguasa. Tujuannya bukan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk menciptakan efek jera dan membungkam suara-suara sumbang.
-
Manipulasi Peraturan dan Proses Hukum: Perubahan undang-undang atau peraturan secara mendadak, interpretasi hukum yang dipaksakan, atau penggunaan celah hukum untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu juga merupakan bentuk politisasi. Ini bisa terlihat dalam proses legislasi yang dipercepat tanpa partisipasi publik memadai, atau putusan pengadilan yang kontroversial di tengah isu politik panas.
-
Intervensi dalam Pengangkatan dan Promosi: Proses rekrutmen dan promosi hakim, jaksa, polisi, hingga pejabat di lembaga pengawas seringkali tidak luput dari intervensi politik. Penempatan individu yang loyal pada kekuasaan di posisi-posisi kunci penegakan hukum dapat melemahkan independensi dan objektivitas institusi tersebut.
-
Pemanfaatan Lembaga Hukum untuk Agenda Politik: Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, atau Kepolisian, yang seharusnya independen, dapat dimanfaatkan untuk memuluskan agenda politik. Penyelidikan atau penetapan tersangka dalam kasus korupsi, misalnya, bisa saja disesuaikan dengan momentum politik tertentu.
Dampak Buruk Politisasi Hukum
Politisasi hukum memiliki dampak yang sangat merusak bagi sendi-sendi bernegara:
- Erosi Kepercayaan Publik: Ketika masyarakat melihat hukum tidak lagi imparsial, kepercayaan terhadap sistem peradilan dan pemerintah akan terkikis. Ini bisa memicu apatisme atau bahkan kemarahan publik.
- Melemahnya Demokrasi dan Supremasi Hukum: Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa supremasi hukum yang kuat. Politisasi hukum meruntuhkan prinsip check and balances, membiarkan kekuasaan eksekutif atau legislatif bertindak tanpa kontrol efektif.
- Ketidakpastian Hukum dan Iklim Investasi: Investor membutuhkan kepastian hukum. Jika hukum mudah diintervensi atau diubah demi kepentingan politik, maka iklim investasi akan menjadi tidak stabil, menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Pemusnahan Semangat Kritis dan Partisipasi Publik: Ancaman kriminalisasi atau jeratan hukum akan membuat masyarakat takut untuk berpendapat atau berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemerintah, yang pada akhirnya membahayakan kebebasan berekspresi.
Studi Kasus (Implisit) dan Contoh Umum di Indonesia
Sejarah politik Indonesia telah beberapa kali menunjukkan bayang-bayang politisasi hukum. Dari kasus-kasus korupsi besar yang penanganannya terkesan lambat atau bahkan mandek jika melibatkan figur tertentu, hingga penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membungkam kritik di media sosial. Perselisihan hasil pemilihan umum yang seringkali berakhir di meja hijau dengan tudingan intervensi, serta konflik agraria atau sengketa bisnis yang melibatkan kekuatan besar, kerap kali memunculkan dugaan adanya "pesanan" politik di balik putusan hukum. Meskipun sulit dibuktikan secara gamblang, pola-pola ini terus berulang dan meninggalkan tanda tanya besar di benak publik.
Jalan ke Depan: Mengembalikan Marwah Hukum
Mengatasi politisasi hukum bukanlah tugas mudah, tetapi mutlak diperlukan demi masa depan Indonesia yang adil dan demokratis. Beberapa langkah kunci meliputi:
- Memperkuat Independensi Lembaga Peradilan: Bebaskan hakim dari segala bentuk intervensi, baik dari eksekutif, legislatif, maupun kelompok kepentingan. Mekanisme seleksi dan promosi harus transparan dan berbasis meritokrasi.
- Peningkatan Integritas Aparat Penegak Hukum: Reformasi internal di kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus terus digalakkan untuk menanamkan budaya anti-intervensi dan berintegritas tinggi.
- Pendidikan Hukum dan Kesadaran Publik: Masyarakat perlu memahami hak-hak mereka dan bagaimana hukum seharusnya bekerja, sehingga mereka dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap praktik-praktik politisasi.
- Pengawasan yang Efektif: Lembaga pengawas internal dan eksternal harus diberi gigi untuk menindak tegas pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang di ranah hukum.
- Komitmen Politik Kuat: Pemimpin politik harus memiliki kemauan dan komitmen untuk tidak mengintervensi atau memanfaatkan hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan menjunjung tinggi supremasi hukum.
Kesimpulan
Ketika hukum menjadi alat politik, ia kehilangan esensinya sebagai penjaga keadilan dan berubah menjadi instrumen penindasan. Di Indonesia, tantangan ini nyata dan mendesak untuk diatasi. Mengembalikan marwah hukum berarti mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat fondasi demokrasi, dan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Ini adalah perjuangan panjang yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak: pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan setiap individu yang percaya pada prinsip keadilan. Masa depan Indonesia yang adil dan beradab sangat bergantung pada kemampuan kita untuk membebaskan hukum dari belenggu kepentingan politik.