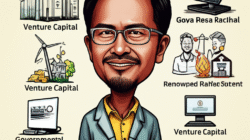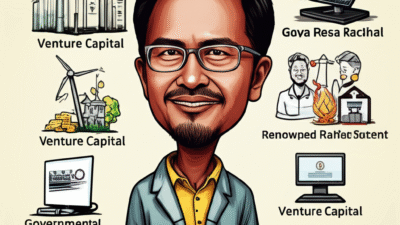Tanah Air, Darah Perlawanan: Bentrokan Agraria dan Keteguhan Adat dalam Menjaga Pusaka Leluhur
Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia, tanah bukan sekadar hamparan fisik tempat berpijak. Ia adalah rahim kehidupan, sumber identitas spiritual dan budaya, penyedia pangan, obat-obatan, hingga makam para leluhur. Tanah adalah "ibu bumi," warisan tak ternilai yang harus dijaga dan diwariskan ke generasi mendatang. Namun, di balik makna sakral ini, terbentang kenyataan pahit: tanah seringkali menjadi arena "peperangan" tak kasat mata yang dikenal sebagai bentrokan agraria, di mana komunitas penjaga tanah berhadapan dengan kekuatan korporasi dan kepentingan pembangunan yang rakus.
Bara Konflik Agraria: Akar dan Wajahnya
Bentrokan agraria adalah persinggungan klaim dan kepentingan atas sumber daya tanah dan alam, yang seringkali berujung pada kekerasan dan perampasan hak. Konflik ini tidak muncul begitu saja, melainkan berakar pada sejarah panjang ketidakadilan, mulai dari warisan kolonialisme yang mengabaikan hak-hak adat, tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, hingga ambisi pembangunan yang mengesampingkan keberadaan masyarakat di wilayah tersebut.
Para pihak yang terlibat dalam bentrokan ini memiliki kesenjangan kekuatan yang timpang. Di satu sisi adalah masyarakat adat dan petani kecil yang bersenjatakan kearifan lokal dan ikatan emosional dengan tanah. Di sisi lain, mereka menghadapi korporasi raksasa di sektor perkebunan (sawit, HTI), pertambangan, properti, hingga proyek infrastruktur negara yang didukung modal besar, jaringan politik, dan seringkali aparat keamanan.
Tanah: Jiwa, Bukan Sekadar Komoditas
Inti dari "peperangan" publik adat dalam bentrokan agraria adalah perbedaan fundamental dalam memandang tanah. Bagi korporasi atau negara, tanah seringkali dilihat sebagai komoditas, aset ekonomi, atau ruang untuk dieksploitasi demi keuntungan dan pembangunan semata. Luasnya hamparan hutan atau lahan kosong adalah peluang investasi yang siap dikonversi.
Sebaliknya, bagi masyarakat adat, tanah adalah entitas hidup yang terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan. Hutan adalah lumbung pangan dan apotek hidup. Sungai adalah sumber air suci. Gunung adalah tempat bersemayam roh leluhur. Kehilangan tanah berarti kehilangan identitas, sejarah, mata pencaharian, bahkan keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas. Inilah mengapa mereka rela berkorban, bahkan nyawa, untuk mempertahankannya.
"Peperangan" dalam Berbagai Rupa
Istilah "peperangan publik adat" dalam konteks ini bukan selalu merujuk pada pertempuran fisik bersenjata, melainkan sebuah perjuangan multidimensional yang tiada henti. Bentuk perlawanan mereka sangat beragam:
- Perlawanan Hukum: Melalui jalur pengadilan, gugatan kelembagaan, atau advokasi kebijakan untuk pengakuan hak-hak adat.
- Aksi Langsung: Demonstrasi damai, blokade jalan atau akses perusahaan, pendudukan kembali lahan, hingga ritual adat yang menegaskan kepemilikan.
- Perlawanan Kultural: Melestarikan bahasa, tarian, lagu, dan cerita rakyat yang mengikat mereka dengan tanah, serta melakukan upacara adat untuk memperkuat identitas dan ikatan komunal.
- Advokasi dan Jaringan: Membangun aliansi dengan organisasi non-pemerintah (LSM), akademisi, media, dan komunitas lain di tingkat lokal, nasional, hingga internasional untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami.
- Ekonomi Alternatif: Mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan atau ekonomi lokal yang mandiri sebagai bentuk perlawanan terhadap model ekonomi ekstraktif.
Namun, perjuangan ini seringkali dibayar mahal. Kriminalisasi aktivis, intimidasi, kekerasan fisik, pemutusan akses terhadap sumber daya alam, hingga pembakaran rumah dan fasilitas umum menjadi risiko yang harus mereka hadapi. Banyak pejuang agraria yang dipenjara, dianiaya, bahkan kehilangan nyawa dalam membela tanahnya.
Mencari Titik Terang: Jalan Menuju Keadilan Agraria
Bentrokan agraria dan "perang" publik adat adalah cerminan dari kegagalan negara dalam menjamin keadilan agraria dan melindungi hak-hak dasar warganya. Untuk mengakhiri siklus kekerasan ini, diperlukan langkah-langkah konkret:
- Pengakuan dan Perlindungan Hak Adat: Negara harus secara penuh mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat mereka, termasuk melalui legislasi yang kuat dan proses pemetaan yang partisipatif.
- Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan Tanpa Paksaan (PBDITP): Setiap proyek pembangunan atau investasi di wilayah adat harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat secara sukarela, tanpa paksaan, dan berdasarkan informasi yang lengkap.
- Penyelesaian Sengketa yang Adil: Membangun mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang independen, transparan, dan berpihak pada keadilan, bukan pada kekuatan modal.
- Penegakan Hukum yang Berpihak: Aparat penegak hukum harus bersikap netral dan adil, tidak menjadi alat bagi kepentingan korporasi atau pihak kuat lainnya.
- Reformasi Kebijakan Agraria: Merombak kebijakan yang tumpang tindih dan membuka celah bagi perampasan tanah, serta mendorong redistribusi tanah kepada petani gurem dan masyarakat yang membutuhkan.
Bentrokan agraria bukan sekadar catatan kelam dalam pembangunan, melainkan sebuah panggilan keras untuk refleksi. Perjuangan masyarakat adat dalam menjaga tanah adalah perjuangan kita semua – demi kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan masa depan yang berkelanjutan. Suara mereka adalah suara bumi yang merintih, menuntut keadilan, pengakuan, dan perlindungan atas pusaka yang tak ternilai harganya. Mereka adalah penjaga terakhir yang berdiri teguh di garis depan, memastikan bahwa tanah air kita tetap menjadi sumber kehidupan, bukan sekadar ladang keuntungan.